Hari, tanggal : Selasa, 10 Juni 2014
Tempat : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)
Tempat : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)
09.06
Akhmad Nasir
Kami akan segera mulai. Kami persilakan teman-teman yang hadir untuk menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan.
Teman-teman yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang dalam acara diskusi ini. Kita nanti akan membahas soal bagaimana kita sebagai publik, masyarakat, melihat media memberitakan bencana. Kita akan melakukan ini sampai nanti pk 12.00. Sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan paparan untuk menjadi pemantik diskusi. Sebelumnya, kita nanti akan mengikuti beberapa rangkaian acara.
Pertama, akan ada kata sambutan dari tuan rumah BPPTKG. Kegiatan ini kerjasama antara BPPTKG dan JALIN Merapi. BPPTKG akan memberikan kata sambutan. Untuk pemanasan, kita akan jalan-jalan dulu. Teman-teman yang belum pernah tahu, bagaimana Merapi diamati dan dipantau dari waktu ke waktu, kesempatan kali ini bisa digunakan untuk melihat dapurnya BPPTKG. Ada ruang pemantauan, bisa untuk pemanasan dijelaskan. Ada pemandu untuk menjelaskan. Setelah itu kita akan kembali di sini dan memulai diskusi.
Begitu kira-kira rangkaian kegiatannya. Pertama kami persilakan Mas Cholik menyampaikan kata sambutan mewakili BPPTKG.
Cholik
Terima kasih. Salam.
Mas Ahmad Arif dari KOMPAS yang kami hormati dan komunitas yang mengelola media tentang Merapi. Saya mohon maaf seharusnya Bapak Subandriyo yang akan membuka acara diskusi pagi ini. Saat ini beliau masih di Dinas PU dalam acara presentasi tentang mitigasi di Merapi. Beliau sekitar pk 10.00 akan mengusahakan akan datang ke sini dan gabung dengan kita.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang di BPPTKG. Dulu kantor ini bernama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK). Sejak Februari 2013, kantor kami berganti nama menjadi Kebencanaan Geologi. Cakupan tugasnya tidak hanya gunungapi, juga tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Kami sudah memasang alat pemantauan untuk tanah longsor juga selain di Gunungapi Merapi, seperti di Purworejo dan Kebumen.
Acara ini diinisiasi dari diskusi kecil kami dan JALIN Merapi. Kami sering kerepotan ketika ada berita tentang Merapi yang sering dipolitisasi dan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Kami sering kewalahan. Diskusi kami dengan teman-teman di JALIN Merapi, bagaimana agar di kemudian hari tidak muncul gejala itu lagi di media mainstream.
Diskusi ini akan berseri. Tahap ini tidak ada media mainstream, tetapi media komunitas. Diskusi ini diawali dengan membangun pemahaman tentang apa yang terjadi di media massa. Ada mas Ahmad Arif dari jurnalis yang menulis Ekspedisi Cincin Api di KOMPAS. Beliau akan berbagi, di satu sisi sebagai jurnalis, dan sisi lain sebagai relawan.
Narasumber kedua Mas Jenarto yang akan berbagi tentang pemberitaan yang salah dari media massa dan dampaknya kepada masyarakat.
Saya hanya ucapkan selamat datang. Pak Subandriyo yang akan tetap membuka dan mengikuti diskusi kita nanti. Kita bisa lanjut ke ruang monitoring. Selamat datang dan selamat berdiskusi. Semoga yang kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi masyarakat di lereng Merapi dan masyarakat umum.
Akhmad Nasir
BPPTKG sebagai tuan rumah sudah memberikan ucapan selamat datang. Kita akan mulai jalan-jalan ke ruang pameran dan monitor. Kita mulai dari depan, dipandu oleh Mas Cholik.
09.17
09.54
Akhmad Nasir
Teman-teman dipersilakan mengambil kopi dan snack dan dibawa ke tempat duduk masing-masing.
09.59
Sebelum kita mulai acara inti, telah hadir Bapak Subandriyo yang akan membuka acara ini, setelah kita sudah jalan-jalan. Kepada Bapak Subandriyo dipersilakan.
Subandriyo
Salam,
Selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman jurnalis pemerhati Merapi yang kami cintai. Saya sebenarnya tidak tahu disuruh membuka itu maksudnya apa. Saya mencoba mengira-ngira jurnalisme sehat itu bagaimana, untuk siapa, oleh siapa? Jurnalisme itu alat. Tentu saja yang disebut dengan jurnalisme sehat itu yang menyehatkan masyarakat, secara psikologis. Dalam pengertian bencana terutama dari aspek psikologis ketika masyarakat menerima informasi itu akan lebih tenang dan bisa melakukan respon dan antisipasi aktivitas Merapi secara lebih efektif, teruur, tanpa ada kepanikan. Walaupun kita tak jamin masyarakat tidak panik, tapi dengan landasan pemahaman aktivitas Merapi yang baik, masyarakat akan lebih tenang. Jurnalisme yang sehat itu yang menenangkan warga di sekitar Merapi.
Teman-teman jurnalis yang saya cintai, berbicara Merapi sangat kompleks. Ada banyak aspek di Merapi. Ketika Merapi bergolak, gaungnya sangat besar. Merapi berbeda dengan gunungapi lain. Status aktivitas gunungapi lain, kita bisa lihat implikasinya tidak luas. Gunungapi Ijen, status waspada dan siaga, sudah dua tahun lebih dan tidak ada implikasi luas. Kemarin Merapi status Waspada saja responnya sudah sangat luas. Bagi kami tidak ada masalah karena memang tidak semua harus sama. Hal yang penting masyarakat harus paham. Saya pun mengikuti diskusi di media sosial yang sering mengarah ke pribadi saya juga. Ada perbedaan dalam interpretasi situasi suatu gunungapi itu biasa, tidak tunggal. Setiap ahli akan ada pendapat berbeda. Di internal kami sendiri pun ada perbedaan yang tajam dalam membahas Merapi. Informasi prediksi itu tidak unik, dalam pengertian pasti benar dan tunggal. Dalam filosofi geofisika, kami hanya mengukur parameter kimia dan fisika saja. Dalam analaogi matematika, kita mengintegralkan sesuatu, yang harus menambahkan variabel “c” sebagai ketidakpastian. Hal inilah yang menjadi konsumsi menarik bagi jurnalis, ketika para ahli berbeda pendapat. Namun, dampaknya yang tidak menarik. Masyarakat menjadi bingung.
Ke depan, informasi tentang status, seharusnya tunggal, apalagi dalam konteks peringatan dini. Perbedaan boleh ada dalam proses, tetapi harus tunggal dalam keputusan. Kita boleh boleh berbeda pendapatan di proses yang terjadi. Dalam penentuan status yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, kita harus ikuti.
Ada sedikit koreksi, kadang sumber berita tentang Merapi, Badan Geologi ingin sumbernya satu dari mereka. BPPTKG itu seperti sumber lokal saja. Namun, sumber informasi seharusnya tetap menggunakan nama Badan Geologi. Saya sebagai Kepala BPPTKG bisa disebutkan, tetapi sumber informasi formal tetap dituliskan Badan Geologi saja. BPPTKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana geologi (PVMBG) dan sebagaimnya itu lembaga yang sama dalam satu kementerian. Jadi, lebih baik ke depan ditulis Badan Geologi saja dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kita berharap jurnalisme yang sehat bisa menjadikan masyarakat ketika menerima informasi bisa tetap tenang.
Diskusi saya buka. Terima kasih. Salam.
Akhmad Nasir
Terima kasih. Tadi sudah disampaikan harapan Pak Subandriyo tentang peran media dalam pemberitaan bencana. Kita akan lanjutkan acara diskusi kita. Saya akan mengundang dua narasumber yang akan paparkan hal-hal untuk diskusi kita. Pertama Mas Jack dari Radio Komunitas Lintas Merapi FM. Narasumber kedua Mas Ahmad Arif dari KOMPAS.
Acara diskusi kita ini sebenarnya baru langkah awal. Dari istilah jurnalisme sehat ini karena mungkin menurut penyelengara, situasi jurnalisme saat ini sedang tidak sehat. Bagaimana agar jurnalisme tentang Merapi ini bisa sehat. Kita sebelum mengobati, kita harus tahu dulu sakit dan penyebabnya apa, sebelum kita bisa cari metode atau cara untuk menyembuhkannya.
Jadi, siang ini kita akan meminta Mas Jack dari Lintas Merapi FM di Deles, Klaten yang berjarak 4,5 KM dari puncak Merapi. Radio komunitas ini juga bagian dari JALIN Merapi yang dikoordinatori oleh pendiri radio komunitas ini. Kita minta Mas Jack menceritakan pengalaman dalam mengelola media komunitas, dan kenapa itu penting. Padahal, sudah ada banyak media yang memberitakan Merapi. Mas Jack juga bisa menceritakan dampak yang muncul ketika ada pemberitaan yang tidak benar tentang Merapi dari media.
Pada bagian berikutnya, Mas Ahmad Arif, sebagai bagian dari media mainstream. Kita ingin tahu dari beliau, bagaimana cara kerja media massa dalam memberitakan bencana. Mas Ahmad Arif juga menulis buku Jurnalisme Bencana dan Bencana Jurnalisme. Kita ingin tahu itu apa dan kenapa itu terjadi. Bagaimana kita bisa ikut memperbaiki situasi itu.
Terakhir, sesi rekomendasi sebagai inti. Rekomendasi ini yang akan kita bawa di rangkaian diskusi selanjutnya. Kita berupaya bisa hadirkan dalam forum pemimpin redaksi. Sesi ini sebagai sesi menjaring aspirasi, dari kita, baik warga maupun pegiat media. Selain radio komunitas, ada juga pegiat OPRB, perwakilan pemerintah desa. Juga hadir teman-teman dari pers mahasiswa, pengelola akun media sosial, dan akademisi. Kita harapkan bisa muncul rekomendasi yang kuat untuk mendorong sehatnya jurnalisme bencana.
Kepada Mas Jack dipersilakan.
Jack Jenarto
Salam.
Saya pegiat Radio Komunitas Lintas Merapi FM. Mengenai informasi, terkait dengan media, kami pada 2006 dicap sebagai provokator, pembangkang. Sebabnya, oleh teman-teman media yang memberitakannya sebagai media sesat, kami juga melihat pemerintah penanganan bencana juga keliru. Pada tahun 2006, pengungsian dilakukan sbeleum waktunya. Teman-teman Lintas Merapi FM saat itu sudah belajar bahwa evakuasi dilakukan pada saat status “Awas”, padahal situasi itu masih “Waspada”. Kami dianggap pembangkang dan dianggap provokasi masyarakat.
Masyarakat lebih percaya pemerintah dan lihat radio komunitas sebagai gerombolan yang tidak jelas. Pada tahun 2010, kami bisa menunjukkan bahwa radio komunitas bisa berperan baik di ranah onair maupun di offair. Namun, kami juga terkendala lagi, di 2014 ini situasi unik. Teman-teman media banyak yang dalam penggunaan istilah saja kami lihat tidak benar. Sampai saat ini, oleh masyarakat menjadi penyebab kebingungan. Untuk menjelaskan, kami harus sampai mendatangkan BPPTKG untuk menjelaskan langsung kepada masyarakat.
Khususnya untuk Desa Sidorejo sudah banyak yang sudah memahami Merapi dan ancamannya. Namun, untuk desa penyangga dalam konteks desa bersaudara, banyak yang heboh sendiri karena pemberitaan media yang tidak tepat. Kami bergiat seperti biasa di KRB III, tapi desa di bawah sudah heboh dan sudah sibuk persiapan. Di Klaten, ada persiapan memasang CCTV di alur Kali Woro oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten. Bukannya itu tidak penting, tapi kami lihat yang dipasang oleh BPPTKG itu sudah cukup.
Media ini juga merangkul komunitas, sehingga bisa membuat judul-judul baru. Komunitas-komunitas baru yang banyak gunakan media sosial ini banyak yang tidak mengunggah fakta, tetapi opini. Ketakutan kami bahwa hal ini akan menjadi pengotakan komunitas/masyarakat. Masyarakat akan bingung jika terjadi letusan, masyarakat harus menurut kepada siapa. Di Cangkringan dan Klaten, pasca 2010 ini muncul ratusan komunitas yang mengklaim paling akurat menginformasikan Merapi. Namun, sayangnya, informasinya tidak sehat, karena sering sumbernya dihilangkan. Jadi, masyarakat yang membaca jadi bingung, sumber informasi ini dari mereka sendiri atau dari sumber yang benar.
Kami punya beban besar di Lintas Merapi FM. Pemerintah sendiri mendukung komunitas-komunitas baru tadi yang merasa paling hebat dalam menginformasikan Merapi. Pemerintah mulai memberikan fasilitas, sehingga ada persaingan tidak sehat. Ada puluhan radio pancar ulang. Ada banyak pegiat yang sebenarnya sama dan saling kenal, tapi saat di udara sering sok tidak saling kenal. Masyarakat jadi bingung.
Berita di TV dan koran, foto lama sering muncul lagi bahkan di berita 2014. Di TV ada tayangan orang ke pasar naik pick up saja disebut masyarakat sudah mengungsi. Rujukan masyarakat nomor satu memang media TV sebagai sumber informasi. Teman-teman radio komunitas, setelah status Normal lagi, kita sering terjun ke RT/warga untuk menyampaikan agar masyarakat lebih kritis, bukan anti TV. Warga harusnya menjadi sumber informasi utama tentang Merapi, bukan media massa. Sering muncul pertanyaan sederhana, “Mengapa di TV belum ada?” sehingga informasi yang dekat justru dianggap tidak valid daripada informasi dari TV.
Kita sudah kenal Merapi, tapi masih punya tantangan bahwa warga masih tergantung dengan TV. Dulu tahun 2006 masyarakat banyak yang punya radio FM. Kini minat masyarakat sudah semakin menurun, sekitar 40% saja dari konten siaran kita. Jadi, kami perbanyak juga kegiatan offair. Selain kami juga ada radio komunitas di Desa Balerante juga, ada dua. Namun, teman-teman belum ada kesepakatan dalam menginformasikan Merapi. Sumbernya sama tapi cara menginformasikannya berbeda. Pengkotakan antar komunitas terjadi.
Pada wilayah Boyolali bagian barat, justru rujukan informasi Merapi bukan teman-teman relawan Boyolali, tetapi ke kami. Kami ini ajak BPPTKG untuk ke daerah Sangup yang masyarakatnya tidak punya pengetahuan PRB sama sekali. Komunitas seperti itu penting untuk ditingkatkan pengetahuannya. Sebenarnya di sana ada banyak relawan juga yang suka aktif menginformasikan Merapi.
Komunitas-komunitas yang bermunculan sering berlomba untuk menginformasikan Merapi untuk mendapatkan respon, walaupun sering hiperbolis. Hal itu banyak terjadi di Klaten dan juga mulai tampak di Boyolali. Hal ini diperparah dengan tindakan pemerintah yang tidak tepat karena muncul kesenjangan yang mendorong adanya konflik sosial. Di Desa Sidorejo, untuk membangun titik kumpul sementara saja susah karena informasinya salah kaprah, misal KRB tidak boleh dibangun titik kumpul dan sebagainya. Jadi, di Balai Desa Sidorejo ada bangunan titik kumpul yang mangkrak karena BPBD Klaten yang tidak tepat memaknai informasi.
Aktivitas masyarakat yang bergiat biasa. Namun, ketika status Waspada kemarin, sebagian masyarakat menganggur karena was-was, khawatir dengan situasi. Mereka banyak lihat TV karena berita di TV sangat heboh. Tidak semua seperti itu, justru masyarakat di luar KRB. Warga di KRB atas, bukan mentang-mentang dekat ancaman dan lebih tahu, tapi mereka sudah belajar terus secara kotinu. Pembelajaran ini juga ke anak-anak.
Kami pun takut jika informasi yang tidak tepat, misal oleh BPBD, akan mengadakan simulasi tentang pengungsian Merapi ke anak-anak. Kami takut hal itu terjadi karena belum saatnya anak-anak ditakuti dengan isu Merapi. Cara yang tepat adalah mendidik anak-anak untuk mengenali Merapi, bukan takut dan lari dengan Merapi. Jika BPBD Klaten mau adakan simulasi evakuasi untuk anak-anak SD, kami khawatir akan muncul persepsi yang salah. Anak-anak Kancing kami kenalkan tentang sungai tempat aliran banjir dan penanaman pohon. Hal itu efektif untuk kenalkan Merapi. Sementara, pemerintah lebih suka memilih jenis kegiatan yang laku apa. Jangan kenalkan Merapi itu jahat, terutama kepada anak-anak.
Akhmad Nasir
Tahun 2006 dicap provokator. Tahun 2014 mungkin dicap pimpinan provokator.
Mas Jack sudah gambarkan situasi lapangan. Kini tidak kurang informasi, tetapi banyak sumber informasi, malah jadi bingung. Informasi yang tidak tepat ini tidak hanya dari media massa, tapi juga pegiat media komunitas, baik itu radio komunikasi maupun media sosial. Kita bisa lihat apa yang terjadi dan akibat yang dirasakan masyarakat.
Mas Jack sudah gambarkan situasi lapangan. Kini tidak kurang informasi, tetapi banyak sumber informasi, malah jadi bingung. Informasi yang tidak tepat ini tidak hanya dari media massa, tapi juga pegiat media komunitas, baik itu radio komunikasi maupun media sosial. Kita bisa lihat apa yang terjadi dan akibat yang dirasakan masyarakat.
Berikutnya Mas Ahmad Arif.
Ahmad Arif
Senang bisa kembali ke Yogyakarta. Saya sekolah di sini dan tugas satu tahun di Yogyakarta, sebelum ke Aceh. Saya akan cerita jurnalisme dan bencana secara nasional, lalu sedikit informasi riset saya di Jepang. Saya ingin lebih banyak diskusi.
“Jurnalisme Sehat dan Menyehatkan” atau “Jurnalisme Sesat dan Menyesatkan”.
Saya ingin sedikit refresh. Saya ada di Aceh sebelum tsunami 2004. Satu minggu sebelum tsunami saya di Medan untuk istirahat. Tsunaki saat itu terbesar yang tercatat di Indonesia. Saya kemudian kembali ke Aceh dan bertuags 3 tahun di sana. Wartawan yang meninggal di Aceh mungkin terbanyak dalam sejarah pers. Teman wartawan yang ikut liputan konflik di Aceh juga menjadi korban.
Wartawan juga menjadi kelompok rentan dalam bencana. Ada teman wartawan yang juga kehilangan keluarganya ketika sedang meliput tsunami yang dikira banjir biasa, Dia memang dapat kepuasan batin sebagai wartawan foto, tapi ada kehilangan besar yang dia rasakan. Hal yang sama terjadi ketika wartawan juga kurang memiliki pengetahuan tentang bencana, seperti ketika ada wartawan masuk ke zona bahaya erupsi gunungapi.
Pengalaman saya tiga tahun di Aceh lebih sebagai pengakuan dosa, otokritik dalam praktik jurnalisme di Aceh. Jurnalisme bencana bisa jadi bencana baru. Ada beberapa catatan dalam praktik di Aceh saat itu. Kabar buruk bagi media memang jadi kabar baik bagi media. Sampai sekarang itu masih dominan. Kita akan lihat konsistensinya hingga saat ini. Bencana juga jadi komoditi, tidak hanya bagi media massa, juga media sosial. Kesedihan juga dieksploitasi.
Ada beberapa pertanyaan yang bersifat eksploitas, yang saya catat dari pertanyaan di TV dalam kejadian gempa Padang. Saya tanya redaksi TV itu dan memang diajwab hal itu ditujukan untuk membangun dramatisasi dan mendorong bantuan. Itu asumsi yang dibangun oleh redaksi.
Kita bisa kuliti sama-sama. Dalam industri media ada banyak bias. Dari asalnya media itu cemar. Praktik itu sangat mengemuka sekarang ketika media sangat sarat dengan kepentingan politik pemilik medianya. Saat ini kita lihat media di Indonesia, sulit menemukan media yang netral. Ada kecenderungan media di Indonesia dimiliki oleh penguasa tunggal atau pemegang saham mayoritas.
Menarik melihat praktik-praktik adanya corporate social responsibility (CSR) terselubung, ketika media juga menyalurkan bantuan. Dramatisasi di media juga karena media massa terlibat dalam penyaluran bantuan. Hal ini masif dalam kejadian tsunami 2004 dan juga di Merapi. Kompas pun juga masih mempertahankan Dana Kemanusiaan Kompas walaupun saya terus kritik.
Media massa tidak selalu mengawal proses pemulihan/rehabilitasi pasca bencana yang sebenarnya vital juga. Selain itu, ada bias desentralisasi dalam pemberitaan. Misal, kejadian Mentawai yang berlangsung berbarengan dengan Merapi menjadikan Mentawai hampir terlupakan. Situasi pascabencana juga berpotensi besar menjadi bencana kembali. Sembilan bulan usai erupsi Sinabung, itu sebenarnya menjadi puncak krisis karena proses yang lama. Berbeda dengan Merapi yang warganya mungkin lebih punya resiliensi dibandingan dengan Sinabung. Di sana, PVMBG sudah persilakan pulang, tapi warga tidak berani pulang, selain karena memang ada masalah infrastruktur. Ada banyak hal tentang konflik dan korupsi pada situasi pascabencana. Hal ini juga harus dikawal oleh media massa.
Ada juga praktik di Aceh, banyak wartawan yang menyeberang ke lembaga bantuan karena ada uang lebih banyak.
Tendensi bahwa media, baik media massa maupun media sosial, memang cenderung eksploitasi kesedihan. Satu per satu bencana akan bikin kita lupa dengan bencana sebelumnya dan kita tidak belajar.
Saya di Jepang pada hari kedua setelah tsunami 2011. Dengan skala gempa yang hampir sama, korbannya sepersepuluhnya dari yang terjadi di Aceh.
Dari sisi media, ada bedanya. Mereka punya NHK yang dalam UU diwajibkan untuk menyampaikan soal tanggap darurat. Ketika terjadi gempa langsung ada black-out. Dokumentasi terbaik tsunami adalah di media Jepang karena sebelum tsunami datang, TV sudah sorot gelombang yang datang.
Dibandingkan di Aceh, berita pertama 12 jam setelah kejadian, itu pun dengan data yang salah. Di Sendai, jepang, hampir tidak ada jeda dalam pemberitaan. Media Jepang punya hubungan langsung dengan infrastrutur pemantauan bencana dan terhubung dengan lembaga yang berwenang. Media di Indonesia harus andalkan tebengan untuk bisa sampai ke lokasi bencana yang pelosok. Kejadian di Mentawai pun terlambat 1 hari untuk dikabarkan.
Media Jepang cenderung kabarkan semangat untuk bangkit daripada mengabarkan tentang kesedihan. Dalam tiga minggu saya di Jepang, saya tidak lihat sama sekali gambar mayat di TV dan media cetak. Sulit temukan gambar orang menangis. Berita yang ada secara substansi lebih untuk dorong publik untuk bangkit.
Saya ke sana lagi hampir 9 bulan di Jepang. Ada media lokal di dekat Sendai yang parah kena tsunami. Kantor media mereka rusak kena tsunami. Mereka tetap putuskan untuk terbit sore harinya, walaupun harus tulis tangan. Semangat mereka tetap ada. Media ini disebut Media Tulisan Tangan, terbit sampai 6 edisi. Substasni pemberitaannya didesain untuk dorong masyarakat lebih semangat. Misal, pada edisi kedua dituliskan bahwa listrik akan segera dipulihkan. Hal itu untuk dorong semangat pada masyarakat. Editornya akui bahwa memang mereka hindari berita sedih agar masyarakat kuat. Dengan baca berita ini maka mental masyarakat akan terhubung dengan komunitas lain untuk sama-sama bangkit.
Praktik ini pun sering dikritik oleh media barat yang cenderung seperti media di Indonesia. Media Jepang sering dikritik menutupi masalah sebenarnya, seperti kejadian di Fukushima. Media di Jepang, setelah bencana segera membuat pusat riset baru. Misal, usai gempa Tokyo di tahun 1900 awal, mereka membangun pusat studi gempa di Tokyo. Juga usai tsunami 2011, ada pusat studi baru yang dibangun. Jadi, selain media, memang ada budaya dan perspektif masyarakat yang harus dibangun. Saya riset tentang tendesi berita tentang kerusakan yang sedikit dan berita yang rekonstruksi yang lebih banyak.
Bagaimana media meliput bencana? Masalah paling serius adalah minimnya pengetahuan tentang bencana pada pelaku media di Indonesia. Banyak media massa yang juga tak punya SOP dalam peliputan bencana. Saya ingat dalam liputan kejadian di Gunung Salak, ada wartawan yang tak pernah naik gunung akhirnya tersesat. Dulu juga ada TV yang tak bisa bedakan awan panas dengan abu vulkanik. Banyak media yang gunakan lokasi bencana sebagi lokasi magang bagi wartawan baru yang akhirnya salah dalam liputan bencana.
Seharusnya, menurut saya, liputan bencana itu harus diawali denganbelajar dari bencana sebelumnya. Meliput bencana itu sekarang tendensinya hanya meliput kejadian saja. Ada tiga tahap yang harus dilakukan. Pertama, pra bencana untuk doron kesiapsiagaan. Kedua, tanggap darurat. Ketiga, mengawal proses rekonstruksi dan rehabilitasi untuk cegah munculnya bencana baru.
Komunitas juga harus didorong. Masyarakat lupa, jurnalis abai, dan pemerintah katrok, jadikan situasi tidak sehat. Setelah dari Aceh saya banyak terganggung bahwa media sebelum 2004 tidak banyak ingatkan publik tentang potensi ancaman tsunami. Dari riset saya, sebenarnya ada banyak informasi kejadian sebelumnya. Jadi, saya gunakan hal itu untuk adakan ekspedisi Cincin Api Kompas. Sering ditolak pada awalnya karena bencana sebelum kejadian itu tidak dianggap penting. Hal yang menjadi perspektif dominan seperti itu di media mainstream. Realisasinya baru bisa dilakukan di tahun 2011 dengan perspektif bahwa mitigasi itu penting untuk kurangi risiko bencana. Contoh konkrit Jepang, korban hanay 1/10 dibandingkan kejadian yang sama di Indonesia.
Refleksi 10 tahun usai tsunami Aceh, praktik media apakah berubah? Saya kira belum berubah. Misal, ada berita tentang aparat yang berjalan ke kawah Kelud yang sebenarnya tidak menunjukkan fakta bahwa tentara itu tidak ke lokasi letusan. Lalu ada berita foto tentang zona bahaya, tapi diberi judul dengan zona bahaya diterobos. Siapa yang menerobos jika bukan wartawannya. Lalu ada foto warga yang bawa TOA (pengeras suara) untuk awasi dan ingatkan publik agar tidak dekati sungai, justru ditulis bahwa warga tidak patuhi laranga beraktivitas di dekat aliran sungai yang teranca banjir lahar. Jadi, ada ketidaktahuan.
Ada tantangan dan peluang dalam media alternatif atau media komunitas. Saya sudah jadi wartawan lebih dari 10 tahun dan agak pesimis. Dari sananya, dapur media memang bias. Setiap ganti wartawan, akan mulai dari awal ketidaktahuannya. Harus ada upaya secara simultan untuk kuatkan media komunitas. Ini adalah ruang wacana yang harus diperebutkan yang tidak bisa dikuasai oleh media massa mainstream saja.
Media sosial di Jepang dapat porsi yang besar juga. Dengan twitter banyak korban yang bisa diselamatkan usai tsunami. Media mainstream kebanyakan lumpuh, kecuali beberapa radio. Radio komunikasi dan twitter menjadi sangat efektif di sana dan di Merapi sudah dipraktikkan sejak lama. Di Merapi, sangat jelas berdayanya media sosial di Merapi. Kini pun hal itu banyak digunakan oleh kampanye politik.
Kini kita masih gunakan radio komunikasi sebagai media yang paling efektif. Saya yakin media sosial akan semakin maju. Potensi Indonesia di media sosial sangat besar. Sangat digdaya jika itu dipakai dalam ranah ini. Namun, munculnya media baru juga munculkan budaya baru; budaya berbagi dan komentar. Namun, juga bisa muncul berbagi hal yang sesat.
Dengan sistem informasi, bisa ada mapping perilaku yang digunakan untuk riset penataan ruang usai tsunami. Jepang data semua HP dan GPS korban, tentang gerakan warga ketika informasi gempa dan tsunami disampaikan. Hasilnya, setelah gempa, justru banyak orang yang datang ke pantai daripada yang menghindari pantai. Padahal, mereka tahu akan ada tsunami. Ternyata, sebagian rumah orang Jepang di sana di pinggir pantai. Orang yang kerja di tempat yang lebih jauh, mereka akn jemput anak atau istrinya. Mereka jadi korban ketika sedang pergi menjauh dari pantai usai menjemput keluarga. Sistem informasi ini menjadi sangat penting.
Dengan media konvensional, seperti radio pun, informasi sampah atau hoax pun sangat umum. Masalah tentang kesalahan informasi ke publik ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya media massa, juga media sosial. Saringannya adalah individu masing-masing. Saringan di media mainstream sebenarnya sudah ada pada editor. Ini juga peluang yang juga harus diperbaiki. Masyarakat Indonesia kadang belum siap ketika diberi pisau informasi. Media mainstream, media sosial itu juga medan laga untuk berebut ruang. Publik rentang dapat informasi sampah ketika pegiat media sosial dikuasi lebih banyak yang tidak sehat.
Karlina Supeli mengatakan, “Masyarakat kita sering tidak bertanggung jawab dan anonim”. (2013)
Sementara itu dulu dan kita bisa lanjut diskusi.
11.11
Akhmad Nasir
Terima kasih. Mas Arif memaparkan kondisi media, dibandingkan antara Indonesia dan Jepang. Ada banyak hal yang mempengaruhi, dari kesiapan hingga cara pandang. Mas Arif, karena sudah 10 tahun dan capek ajak teman-temannya agar lebih sehat, tapi belum berhasi. Ada harapan pada media alternatif atau media sosial. Walaupun juga ada catatan, jika media mainstream memang cemar dari sananya, media sosial juga punya kelemahan yang perlu dibenahi. Menurut Mas Arif tetap menjadi potensi besar untuk dikembangkan dan diperkuat perannya untuk PRB.
Sesi pertanyaan dan atau usul jika ada hal-hal yang menurut teman-teman penting untuk disampaikan.
Winaryo (PSBA UGM)
Tadi sudah dipaparkan narasumber dengan jelas. Saya hanya usulkan, bagaimanapun juga, ketidaksempurnaan harus disempurnakan. Hal yang sesat dan tidak sehat justru disukai oleh masyarakat. Jika medianya sakit, saya khawatir masyarakat akan komplikasi. Bahaya akan sangat besar.
Saya usul, bahwa media dan juga wartawan sebagai ujung tombak, perlu ada edukasi. Bagaimana masyarakat bisa sehat jika medianya tidak sehat. Dalam rekrutmen wartawan, perlu ada kriteria dan pembekalan khusus untuk desk tertentu, misal dalam desk kebencanaan.
Bisakah ada sertifikasi khusus bagi wartawan yang meliput bencana? Wartawan itu harus punya pemahaman lengkap, fisik dan sosial.
Perlu ada pelatihan-pelatihan untuk wartawan. Tidak semua wartawan paham mekanisme penanggulangan bencana. Pada setiap tahap penanggulangan bencana, ada jenis berita yang akan berbeda.
Tentang radio, distribusi dari stasiun yang ada apakah menyebar melingkar, ataukah dari hulu ke hilir? Radio komunitas yang bersifat lokal ini bisa untuk peringatan dini. Komunitas yang di atas yang pertama kali tahu kejadian di atas. Kejadian di Situ Gintung, masyarakat di sekitar tanggul tahu, tetapi korban banyak yang ada di bawah. Distribusi informasi harus dari hulu ke hilir.
Tria (wartawan)
Pengalaman saya belum begitu banyak daripada Mas Arif. Saya melihat dari peristiwa yang ada di Yogyakarta secara keseluruhan, misal di tahun 2006 ada gempa bumi. Waktu itu saya belum masuk dunia jurnalistik dan belum begitu paham prosesnya. Proses pemulihan di Yogyakarta termasuk bagus dan masalah yang muncul tidak sebanyak di Aceh.
Hal yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan antara media di Indonesia dan Jepang sebenarnya? Tujuannya memang sama, tapi kenapa cara media bisa berbeda? Apa yang menjadi kekurangan di media Indonesia. Yogyakarta juga sudah cukup bagus dalam menginformasikan proses yang berjalan, sejak gempa bumi 2006. Pernah ada kesepakatan di kalangan jurnalis waktu itu untuk stop pemberitaan yang buruk menjadi pemberitaan hal yang baik. Jangan sampai terbangun mindset pada masyarakat bahwa media memunculkan kebingungan.
Ahmad Arif
Saya sebenarnya setuju bahwa wartawan dalam liputan bencana harus dikuatkan. Ada banyak masalah dan hampir tidak ada perubahan signifikan dalam 10 tahun ini. Kesalahan yang sama terulang lagi. Saya pernah beberapa kali melakukan workshop tentang media dan liputan bencana. Saat saya di AJI Jakarta juga sempat membuat wartawan tanggap bencana. Hal yang sama juga saya inisiasi di Aceh dan di Padang dengan Jurnalis Peduli Bencana.
Masalah mendasar media di Indonesia, media kita tidak mengenal spesialisasi wartawan. Wartawan bisa mudah dipindahkan. Misal, saya sudah 10 tahun di bencana, bisa setiap saat dipindahkan ke desk lain yang tidak ada hubungannya dengan bencana. Media di barat, puncak karir wartawan itu ketika menjadi kolumnis karena spesialisasinya. Saya sering bertemu dengan wartawan baru dari media yang sama dalam kejadian bencana yang berbeda.
Akademisi dalam displin komunikasi bisa memasukkan hal ini dalam kurikulum sendiri. Peliputan bencana dan interaksi dengan korban itu harus ada perspektif dan kemampuan yang khusus. Perspektif pengurangan risiko bencana juga harus dipahami oleh media.
Standardisasi dan sertifikasi wartawan itu saya agak pesimistis. Untuk sertifikasi wartawan non amplop saja sangat sulit. Saat saya di Jepang, saya sempat bertanya apakah ada larangan dan kode etik untuk menampilkan tayangan korban dan dramatisasi. Mereka jawab tidak ada larangan. Namun, mengapa tidak dilakukan? Bagi orang Jepang adalah aib besar untuk menampilkan korban bencana yang meninggal. Hal ini terkait dengan budaya dan persepsi masyarakat terhadap bencana. Jika ada dibangun harus pada bagian itu, tetapi harus agak panjang. Larangan media tidak berpihak dalam pemilu saja diabaikan. Padahal, hal itu sudah sangat jelas bahwa media harus tidak berpihak dalam urusan politik.
Saya sepakat bahwa itu harus didorong, tetapi tidak menjamin akan mengubah. Perubahan pada perspektif akan lebih baik. Hukuman sosial dari publik akan lebih baik. Publik yang menghujat media tertentu dan laporan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu cukup efektif, daripada harus buat aturan bahwa media itu harus berubah, walaupun itu tetap harus dilakukan. Pelatihan perlu dilakukan, tetapi pendidikan sejak dalam kampus juga bisa dimasukkan. Namun, itu bukan jaminan, sekali lagi. Sebabnya, media di Indonesia tidak ada spesialisasi. Media cenderung tahu sedikit tapi sok tahu. Media sosial juga punya kerentanan yang sama. Pelatihan untuk pegiat media sosial juga harus sama kuatnya dengan untuk media massa.
Saya tidak bilang juga media di Jepang lebih baik semua dibandingan media di Indonesia. Media di Jepang tidak terlalu kritis terhadap pemerintahnya. Ada kecenderungan media cenderung seragam. Media di Indonesia lebih kritis walaupun beberapa bisa kebablasan. Namun, harus diakui, media di Jepang lebih kuat untuk mendorong resiliensi. Hal ini soal budaya. Jika media selalu beralasan bahwa publik suka dengan informasi gosip. Media akan selalu kemas informasi dengan format seperti itu.
Dalam ekspedisi cincin api, saya usulkan multimedia dan ada halaman tambahan di edisi cetak. Harus cari iklan karena tidak bisa hanya dari redaksi pembiayaannya. Cari sponsor pun sulit karena persepsi perusahaan terhadap bencana hampir selalu negatif. Beda dengan di Jepang, iklan tentang mitigasi bencana itu sangat seksi, misal produk asuransi. Awal ekspedisi cincin api awalnya sulit, walaupun kemudian dapat iklan tapi tidak sehat, dengan iklan rokok. Sebenarnya saya tidak suka, tetapi tidak ada pilihan.
Waktu itu saya bereksperimen dengan Ekspedisi Cincin Api. Konsep awal saya memang akan membuat pemetaan tentang ancaman, antropologinya, dan kepercayaannya. Kami kami ke seluruh 12 tema di Indonesia. Kami ke lapangan ajak peneliti dan ahli. Misal saat ke Kelud saya ajak Pak Surono karena beliau disertasinya tentang Kelud. Kami coba gabungkan konsep komunikasi sains. Bagaimana media bisa menginformasikan pengetahuan sains ke publik agar ruang diskusi yang sebelumnya berat menjadi lebih populer. Kami juga lakukan pendekatan multi media agar bisa lebih mudah dipahami masyarakat. Konten berbahasa indonesia gratis, bisa diunduh diandroid. Konten berbayar hanya edisi Bahasa Inggris.
Di Merapi saya lebih liput tentang daya hidup masyarakatnya, tidak hanya soal aspek bencananya. Kami coba hindari untuk menakit-nakuti, tapi lebih jelaskan risikonya. Kami buat animasi yang tujuannya untuk anak-anak juga. Kami gunakan sumber-sumber resmi, seperti jurnal ilmiah yang telah terverifikasi oleh komunitas ilmiah. Ada gambar dan foto yang seram dan ada yang doron semangat juga. Dengan pendekatan foto 360 derajat, diharapkan bisa ajak publik bisa lebih merasa dekat dengan Merapi. Saya hubungkan dengan sistem kepercayaan yang ada di Merapi dari masa ke masa. Saya tulis juga tentang persebaran candi di sekitar Merapi untuk menunjukkan bahwa memang ada risiko dari Merapi, tetapi masyarakat sejak waktu itu tetap tinggal di dekat Merapi. Ini semua tentang pengetahuan untuk mitigasi ke depan.
Perspektif peliputan yang lebih dominan di persiapan sebelum bencana dan pascabencana itu sebenarnya lebih baik. Peliputan saat bencana sebenarnya sangat tidak efektif. Hal itu justru bisa dilakukan oleh media komunitas, seperti radio komunitas. Hal itu misalnya, terjadi di erupsi Kelud 2014, informasi situasi bisa mereka kabarkan untuk komunitasnya untuk keselamatan. Media komunitas paling efektif di situasi tanggap darurat, salah satunya dengan radio komunitas.
Jack Jenarto
Saya setuju bahwa media punya SOP. Kami juga punya SOP siapa yang mencari informasi dan siapa yang mengabarkan. Kami di Lintas Merapi, informasi kami bisa didengarkan oleh komunitas tidak terbatas dari Klaten, juga dari Sleman. Kami sangat berharap bisa mendapatkan respon balik, sehingga informasi yang kami kabarkan bisa dua arah.
Akhmad Nasir
Ada perbedaan budaya antara media di Jepang dan di Indonesia. Di balik keputusan redaksi ada soal budaya. Kemudian, cara efektif untuk ubah perilaku media mainstream adalah dengan hukuman sosial oleh publik untuk paksa media berubah.
Tahun 2010 ada wartawan TV yang mengabarkan banjir lahar di Magelang. Namun, ada relawan warga yang mengkonfirmasi via twitter bahwa tidak terjadi banjir lahar. Pemimpin redaksi tahu dari timeline dan kemudian menegur wartawannya. Kini di media sosial, bisa ada proses verifikasi dari publik. Ketika ada informasi yang salah, bisa dibully ramai-ramai di timeline. Juga bisa dengan melakukan boikot program tertentu.
Upaya yang sifatnya rekomendasi, selain pelatihan, adalah munculkan peran media komunitas. Media adalah ruang yang harus diperebutkan. Jangan berharap ruang media akan diberikan secara sukarela. Ruang media harus direbut agar bisa lebih sehat.
Tanto Bumi (Kepala Desa Dukun, Magelang)
Kadangkala media komunitas, lebih kalah dengan media yang komersial. Jujur, kebetulan saya juga pemangku wilayah desa. Kesimpangsiuran pemberitaan berdampak pada kepanikan di tingkat warga. Pemerintah gembar gemborkan PRB berbasis komunitas itu belum berhasil. Kesiapsigaan yang terbangun adalah kesiapan yang traumatik. Peran jurnalis itu penting sekali pada hal pemberitaan yang benar. Pada wilayah Dukun dan Magelang belum sampai tahap itu.
Jurnalis itu pintar dalam banyak bidang. Bersama BNPB dan Pusdantin, pernah ada pelatihan dengan jurnalis dan saya ikut terlibat dalam pelatihan. Saya lihat banyak wartawan yang tidak paham soal bencana. Mereka hanya bekerja berdasarkan job.
Penanganan berbasis masyarakat, khususnya jurnalis, di desa kami juga ada radio komunitas K FM. Radio kami masih kalah dengan media komersial. Bagaimana masyarakat agar bisa dan mau mendengarkan itu? K FM satu-satunya media yang mengabarkan kebencanaan.
Pakdhe Senggol (JogjaUpdate)
Saya hendak berbagi pengalaman dari 2010. Kita dari media sosial kebetulan pada waktu itu sekitar 1-2 bulan sebelumnya baru kenal Mas Nasir. Dari sanalah sebenarnya awal interest saya pada keadaan lingkungan Merapi. Pada saat Merapi hampir meletus, saya sudah cukup tahu ada JALIN Merapi. Saya sudah siapkan perangkat. Kebetulan perangkat saya komplit. Begitu JALIN Merapi keluar, berarti ada warning. Saya juga siapkan perangkat di mobil.
Dari sisi informasi, kita kendalanya adalah pada mencari sesuatu yang valid. Pada saat terjadi bencana, terlalu banyak informasi yang masuk. Informasi yang harus kita jawab ke follower kita itu belum tersedia. Misal, contoh, kenaikan status Merapi. Saya banyak dikomplain oleh banyak follower karena BPPTKG belum update di akun twitternya. Walaupun sudah terima foto suratnya, tetapi belum ada di akun twitter @BPPTKG, publik pun membacanya sebagai informasi tidak benar (hoax). Jadi, ketika ada situasi tertentu, informasi harus selalu diteruskan ke semua media. Akun-akun lain juga kadang terlambat. Jadi, kami harus mencari sendiri. Kadang informasi pembanding dicari untuk mendapatkan informasi yang valid, walaupun bukan dari akun resmi.
Jika ada masukan informasi dengan gambar kotak, saya cenderung abaikan gambarnya. Saya cari informasi pembanding dari data yang ada. Saya kerja sendiri dan harus pastikan informasi itu valid. Saya sering sulit memutuskan kapan informasi akan dikeluarkan ketika rujukan kita juga belum mengeluarkan informasi.
Komunitas Merapi sudah saling komunikasi aktif dan bisa jadi patokan. Teman-teman pemantau Merapi memang diakui punya branding image, bahwa merekalah yang paling bisa dipercaya. Pelaku media sosial kemudian akan mendapatkan kepercayaan dari informasi yang bisa didapat dari bio akun twitter. Jadi, ada proses membranding diri secara tidak langsung yang akan membuat publik percaya bahwa informasi dari akun tersebut relatif benar. Jadi, hal itu cukup membantu mengurangi keraguan.
Masalah komunikasi radio swasta niaga/komersial, kita lihat dari 2010 kemarin, informasinya memang masih agak kurang. Saya sempat kabarkan ke Mas Nasir untuk minta slot di radio komersial. Kadang HP kehabisan pulsa dan akses internet yang jelek. Namun, HP biasa pun sekarang ada fungsi radio. Jadi, pada situasi minimal, publik masih bisa dengarkan radio siaran. Ke depan, kita bisa upayakan untuk rekrut media mana saja yang bisa digerakkan untuk dukung proses penanggulangan bencana ini.
Adriani Zulivan
Saya berterima kasih kepada Mas Arif karena saya sangat senang ketika membaca Ekspedisi Cincin Api KOMPAS.
Saya pikir bahwa benar kata Mas Arif, benar yang penting pemberitaan pada masa tanggap darurat itu lebih efektif dilakukan oleh media komunitas.
Apakah bisa kita bisa membangun semacam media camp untuk mengajak pelaku media mainstream ke Merapi? Bagaimana cara untuk mengajak mereka tahu bagaimana situasi dan gerakan warga di Merapi?
Akhmad Nasir
Pertanyaan tentang bagaimana agar informasi valid itu tetap muncul ketika sumber resmi belum mengeluarkan informasi resmi.
Bagaimana teman-teman yang aktif menyampaikan informasi tentang Merapi, juga lebih serius menampilkan biodata dirinya agar publik media sosial bisa paham dan percaya. Hal menarik yang bisa dilakukan adalah kegiatan berbagi antar admin media sosial.
Ahmad Arif
Banyak jurnalis yang tidak paham bencana dan bagaimana agar informasi yang dimunculkan tidak menakutkan. Saya pikir masyarakat Merapi ini sangat berani. Masyarakat Sinabung pun hingga kini banyak yang tidak berani pulang. Trauma yang dirasakan antara masyarakat Sinabung dan Merapi beda, dalam daya resiliensinya. Dibandingkan dengan Jepang pun, masyarakat Indonesia sangat berani. Kita tak bisa mengosongkan ruang di gunungapi. Kita tinggal bagaimana kuatkan masyarakatnya lebih jauh. Aspek budaya dalam bencana itu sangat penting dan justru itu yang kurang diangkat di media massa.
Persepsi media di Jepang dan Indonesia terhadap mayat/korban yang berbeda. Masyarakat Jepang melihat bahwa korban itu ada maka itu adalah kegagalan dari proses penanggulangan bencana dan itu adalah aib. Sementara di Indonesia, dari survei kualititaf di 7 kota rentan bencana di Indonesia, separuh lebih percaya bahwa bencana itu takdir Tuhan dan tak bisa dimitigasi. Lalu, 30% di antaranya percaya bencana bisa dimitigasi, tetapi tetap tergantung takdir. Masyarakat Aceh pun sebenarnya cukup resilien. Kapal korban tsunami di Aceh dimuseumkan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan alam dan kuasa Tuhan. Sementara di Jepang, kapal korban tsunami dihancurkan agar bisa terus berpikir ke depan. Namun, di Jepang, banyak korban yang tertekan dan bunuh diri. Sementara di Indonesia, seperti di Merapi, tampaknya cenderung lebih kuat. Sepertinya tidak ada kasus bunuh diri karena tertekan akibat bencana. Jepang bisa ada kebijakan pengosongan ruang yang terancam gunungapi. Hal itu tak bisa dilakukan di Indonesia.
Indonesia punya pulau-pulau gunungapi. Pulau itu memiliki ribuan warga yang tidak akan bisa dipindahkan. Jadi, kita perlu pahami lebih jauh karakter khas dari setiap daerah. Solusi di Merapi akan berbeda dengan solusi yang bisa dilakukan di Sinabung, Kelud, dan sebagainya. Perlu ada banyak riset sosial tentang kebencanaan, terutama di gunungapi. Bagi saya sebagai wartawan, hasil riset ini sangat penting untuk memahami dan membantu membangun beritanya. Ini pekerjaan rumah bagi komunitas dan akademisi juga.
Problem pada media sosial dan media mainstream seharusnya tidak dalam posisi saling berhadapan. Saya pikir penyakit di kedua media ini akan sama, soal akurasi, soal kecepatan, dan informasi yang sehat atau sesat. Hal yang membedakan hanya modus medianya saja, tetapi hal yang lain akan sama. Media mainstream instansi medianya cenderung mapan dan cenderung mapan, sedangkan media sosial lebih interaktif. Namun, ke depan media sosial akan lebih dominan. Seperti YouTube, kini lebih populer daripada TV ke depan. Dampaknya adalah masyarakat dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Dulu tuntutan itu hanya ada pada pelaku media mainstream, kini akan juga tertuju pada pelaku media sosial. Hal ini tidak bisa dihadap-hadapkan. Penyakit mediamainstream akan ditularkan ke media sosial.
Pelatihan yang kontinu pada media untuk ranah kebencanaan, bisa dimulai dari cara memverifikasi informan sumber informasi. Kemudian perspektif, etika, dan teknis pengelolaan informasi dengan media. Hal ini perlu dilakukan baik pada media mainstream maupun pada media sosial.
Saya pikir, tidak ada salahnya dan mungkin penting ada kegiatan semacam media camp untuk undang wartawan ke lapangan. Hal ini juga tergantung wartawannya, bagaimana membuat mereka tertarik. Seperti apa yang saya lakukan dengan passion saya, akhirnya akan jadi personal, bukan institusional. Saya tetap bisa dipindahkan ke desk mana saja oleh redaksi. Media lain saya pikir sama. Bagaimana kita bisa menanamkan passion seseorang. Ya, salah satunya dengan memperkenalkan dengan realitas yang ada di masyarakat dengan mengajak bertemu dengan komunitas di Merapi. Jadi, ketika mereka akan melakukan peliputan, mereka bisa mulai tahu bagaimana dan kepada siapa dampaknya.
Akhmad Nasir
Saya minta izin perpanjang waktu 5 menit. Teman-teman yang lain bisa sambil makan.
Anton Birowo (UAJY)
Saya lihat salah satu kekuatan di Yogyakarta dan sekitarnya adalah komunitas dengan solidaritas yang kuat. Banyak kelompok yang ingin berperan bagi komunitas yang lain. Bahkan ketika ada kejadian bencana di daerah lain, banyak relawan yang ingin hadir ke lokasi bencana. Namun, sebagian relawan tidak siap dan ada yang jadi korban. Solidaritas ini juga beralih dengan memainkan peran ke pihak lain dengan informasi. JALIN Merapi yang bisa dorong peran banyak pihak yang unya solidaritas dengan informasi.
Bagaimana cara untuk mengelola ini, solidaritas dengan informasi, karena masalah yang ada adalah masalah kita bersama.
Jack Jenarto
Cara pandang bahwa relawan yang harus terjun ke lokasi, pelan-pelan akan kita bangun pemahaman baru. Kemarin relawan dari bawah semua naik untuk menolong. Padahal, sebenarnya komunitas di atas sebenarnya banyak yang sudah bisa menolong dirinya sendiri. Bukannya tidak butuh, tetapi ada gap, sehingga ada yang tidak jelas perannya. Ada banyak relawan yang jarang komunikasi dengan komunitas yang akan ditolong. Jadi, harus ada komunikasi agar ada sinergitas antara komunitas yang perlu ditolong dengan komunitas yang berniat menolong. Hal ini akan jadi bencana baru jika tidak dikelola dengan tepat.
Ahmad Arif
Saya sedang mempersiapkan satu hal, usai pulang dari Sinabung. Saya lihat Merapi punya komunitas yang baik. Hal ini tidak ada di Sinabung karena modal sosialnya belum terbangun. Pada situasi yang lebih mikro, di Merapi juga ada pernik-pernik yang bisa menimbulkan masalah. Sudah saatnya untuk membuat portal bersama yang akan menjadi induknya. Misal di Merapi ada portal bersama yang akan bisa saling mengisi. Jadi, dalam portal bisa menghubungkan antar komunitas.
Kerja-kerja yang kita lakukan semua untuk komunitas. Jadi, semua komunitas harus lebih rendah hati untuk mau saling terhubung. Pengetahuan ini juga penting untuk diteruskan ke komunitas di tempat lain. Teman-teman Merapi misalnya sudah sampai ke Kelud dan Sinabung. Namun, Sinabung saya lihat masih panjang prosesnya. Modal sosial harus dibangun. Jika ada portal besar yang bisa menghubungkan pengetahuan antar pengetahuan ini akan sangat baik. Saya sedang membuat ini secara voluntary. Jika sudah jadi, teman-teman Merapi bisa mengisi paling depan. Intinya, media warga, tetapi saya bawa konsep ada administrator yang bersifat seperti editor untuk memverifikasi data dan informasi yang tepat dan benar. Hal ini penting agar media sosial tidak jatuh pada penyakit yang sama dengan media mainstream.
Saya siap membantu kapan saja karena ini sudah jadi passion saya. Mari sama-sama bergerak ke sana.
Akhmad Nasir
Terima kasih Mas Arif dan Mas Jack, dua narasumber yang cukup lengkap menyampaikan paparan sebagai pemantik diskusi.
Dua point. Cara pandang dalam melihat media mainstream dan media komunitas atau media media sosial, harus tidak dilihat berhadapan, tetapi saling melengkapi agar bisa lebih sehat. Pegiat media komunitas, kita punya tugas besar untuk mendorong peran media komunitas sebagai bagain dari proses pengurangan risiko bencana. Namun, media komunitas harus hati-hati jangan sampai tertular penyakit yang sama yang diidap media mainstream. Perlu ada media yang bisa dipakai bersama agar solidaritas ini bisa terjaga.
Jadi, saya selaku moderator akan menutup sesi ini. Kepada dua narasumber mari kita beri applause. Kita akan tindaklanjuti proses ini dengan pertemuan yang lebih konkrit.
Terima kasih. Salam
12.32
Sumber: http://web.jalinmerapi.net/2014/06/10/rekam-proses-diskusi-jurnalisme-sehat-dalam-penanggulangan-bencana-erupsi-merapi-di-bpptkg-yogyakarta/




















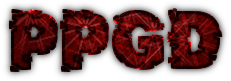
0 komentar:
Posting Komentar